Lemhannas Ajak Masyarakat Pahami Peradaban Masa Depan lewat Gelaran Jakarta Geopolitical Forum V 2021

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini, masyarakat di seluruh dunia sedang menghadapi berbagai problem, mulai dari perselisihan ekonomi politik negara adikuasa, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, hingga kesenjangan sosial. Kemunculan pandemi Covid-19 meningkatkan ambiguitas atas masa depan manusia.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma kontemporer. Sebut saja rasialisme, xenofobia, kapitalisasi budaya yang mengikis nilai-nilai tradisional, serta kebingungan antara spiritualitas dan dogma agama yang memecah belah persatuan.
Selain itu, perkembangan teknologi dan arus modernisasi juga menimbulkan persoalan seperti kerusakan alam. Sementara, bagi Indonesia, mempertahankan identitas nasional juga menjadi tantangan di tengah perkembangan peradaban.
Isu-isu tersebut dibahas dalam Jakarta Geopolitical Forum ke-5 2021 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI). Forum berlangsung selama dua hari, yakni pada Kamis (21/10/2021) dan Jumat (22/10/2021).
Forum yang disiarkan secara langsung dari Studio Kompas TV dan dapat diikuti secara online melalui Zoom tersebut mengusung tema “Culture and Civilization: Humanity at The Crossroads”.
Untuk diketahui, Jakarta Geopolitical Forum merupakan forum intelektual yang menghadirkan para akademisi dan pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membahas situasi dan perkembangan geopolitik dunia saat ini.
Pada hari pertama, Jakarta Geopolitical Forum ke-5 menampilkan dua sesi pleno. Sesi pleno pertama diisi oleh narasumber dari Intercontinental Technology and Strategic Architect Boston Rudy Breighton, Former Director of the Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA) Universitas Boston Profesor Robert W Hefner, antropolog dan budayawan dari Prancis Jean Couteau, dan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Profesor Komaruddin Hidayat.
Sementara, pada sesi pleno kedua, narasumber yang hadir adalah sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert dan Neurosains dokter Roslan Yusni Hasan
Pada pidato pembuka, Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa tema Jakarta Geopolitical Forum kali ini berkaitan dengan era postmodern yang menyebabkan perubahan perspektif dan persepsi terkait pergeseran kekuasaan dan kekuatan di dunia saat ini. Perubahan itu disebabkan oleh budaya teknologi atau tekno-culture.
 Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan kata sambutan.
Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan kata sambutan. Agus mengatakan, dampak perubahan tersebut telah memberi dua pilihan bagi manusia, yakni nilai-nilai kemanusiaan atau kemanfaatan teknologi. Menurutnya, manusia postmodern lebih memilih untuk memandang kehidupan ke depan melalui teknologi dibandingkan masa lalu atau sejarah.
“Singkatnya, teknologi dapat memengaruhi ideologi dan sistem sosial ke depannnya,” tutur Agus.
Kondisi tersebut berdampak pada situasi geopolitik dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, saat ini, Indonesia menghadapi dua masalah yang tidak mudah dalam konteks geopolitik, yakni merawat budaya nasional dan membangun budaya modern untuk kepentingan bangsa.
Oleh karena itu, kata Agus, Jakarta Geopolitical Forum kali ini bertujuan untuk memahami secara lebih baik mengenai masa depan dari peradaban saat ini. Terutama, struktur budaya dan sosial dalam komunitas global.
“Forum ini berupaya menyajikan grand design atau sistem geopolitik secara obyektif yang mencerminkan peradaban dunia ke depannya,” tuturnya.
Sementara, Komisaris Utama PT Telkom Tbk Profesor Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya menyoroti langkah Jepang yang siap menyambut kedatangan masyarakat atau society 5.0. Pasalnya, Jepang menjadi negara pertama yang siap menyambut era masyarakat supersmart itu.
Menurutnya, masyarakat 5.0 akan ditunjang dengan teknologi tinggi dan mampu mengatasi keterbatasan fisik yang saat ini masih dialami oleh masyarakat 4.0. Misalnya, masyarakat 5.0 mampu menyimpan seluruh data melalui ruang penyimpanan secara digital dalam jumlah besar berbasis cloud, tidak lagi melalui hard disk.
“Dengan demikian, ruang cyber akan menjadi solusi sekaligus masa depan bagi masyarakat tersebut. Jika butuh bantuan, masyarakat 5.0 tinggal mengakses data melalui cloud, lalu meminta bantuan artificial intelegent (AI) untuk mengolah data sesuai keperluan. Seperti itulah cara masyarakat 5.0 bekerja,” ujar Bambang.
Menerka masa depan Indonesia
Rudy Breighton yang menjadi narasumber pertama pada sesi pleno pertama memaparkan bahwa penggunaan teknologi atau AI menjadi keniscayaan saat ini. Pasalnya, kecerdasan AI mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara independen.
“Bayangkan AI sebagai seorang manusia yang dapat menyelesaikan berbagai masalah tanpa harus Anda perintahkan,” kata Rudy yang hadir secara virtual dalam forum tersebut.
Rudy menambahkan, saat ini pengaplikasian AI sudah digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan, mulai dari industri hingga militer. Sebut saja mobil tanpa kemudi, Google Assistant, dan penggunaan drone oleh militer Amerika.
Tak hanya itu, pemanfaatan AI juga bisa dilakukan secara luas oleh masyarakat sipil.
“Saat ini, proses automatisasi dengan mengandalkan AI sudah berjalan, tapi banyak orang yang belum menyadarinya. Misalnya, saat kartu kredit hilang dan Anda melaporkan ke pihak bank, AI langsung menindak laporan Anda. Dalam waktu singkat, kartu kredit baru akan sampai ke rumah Anda,” tuturnya.
Terkait bidang pertahanan dan keamanan, Rudy memaparkan pemanfaatan teknologi sudah di depan mata. Ia menjelaskan teknologi yang kini tengah banyak diperbincangkan, yaitu Android Super Soldiers.
Bukti penggunaan teknologi juga dapat dilihat lewat Boston Dynamic Robots, perusahaan pengembang teknologi robotic. Perusahaan ini, kini sudah dapat mengembangkan robot yang dapat menyeimbangkan diri sendiri dan berlari.
Kemudian, ia juga menyampaikan visi Amerika Serikat yang akan mengembangkan automasi di bidang pertahanan, terutama di medan peperangan selain penggunaan drone militer saat ini.
Agar tidak tertinggal, Indonesia perlu visi jangka panjang, infrastruktur strategis, data yang menunjang, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Perubahan tidak menyenangkan, tetapi perubahan akan terjadi, suka atau tidak. Ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak negara,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait spiritualitas dan negara, Profesor Robert W Hefner menjelaskan bahwa peradaban yang ada di dunia bekerja dengan cara saling bersinergi dan melengkapi. Anggapan ini sekaligus menentang gagasan Samuel P Huntington bahwa peradaban saling terisolir dan tidak ada sinergi sehingga menjadi sumber konflik.
Robert melanjutkan, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki banyak kebudayaan harus mampu bersinergi dan saling mengisi.
“Peradaban tidak bisa berdiri sendiri karena mereka saling memengaruhi sampai terwujudnya peradaban baru. Tanpa adanya peradaban muslim, misalnya, peradaban Eropa tak akan mampu melakukan transformasi yang hasilnya sekarang mereka nikmati,” kata Robert.
Terkait sistem demokrasi di dunia, Robert mengatakan bahwa saat ini banyak negara yang mengadopsi sistem demokrasi di Amerika Serikat, yakni dengan memisahkan negara dengan agama. Menurutnya, Indonesia berbeda karena bisa mengembangkan sistem demokrasi sendiri yang lebih cocok dengan kondisinya,
Indonesia, kata Robert, dapat menjadi contoh yang baik karena di sini semua elemen dapat bahu-membahu menjaga demokrasi di bawah Pancasila dan Kebhinekaan. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan baik dengan menjalankan peran negara dan agama secara baik.
“Kolaborasi yang baik dapat berjalan di bawah naungan Pancasila untuk mengakomodasi pluralisme. Ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tapi juga memperkayanya,” tutur Robert.
Masih terkait agama dan negara, narasumber selanjutnya, Jean Couteau menyoroti kemungkinan terjadinya fenomena Gutenberg Sindrom dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Fenomena tersebut adalah keterkaitan pendidikan seseorang untuk meningkatkan otonomi perorangan dan memberikannya kebebasan tafsir yang baru atas kitab suci dan kondisi sosial.
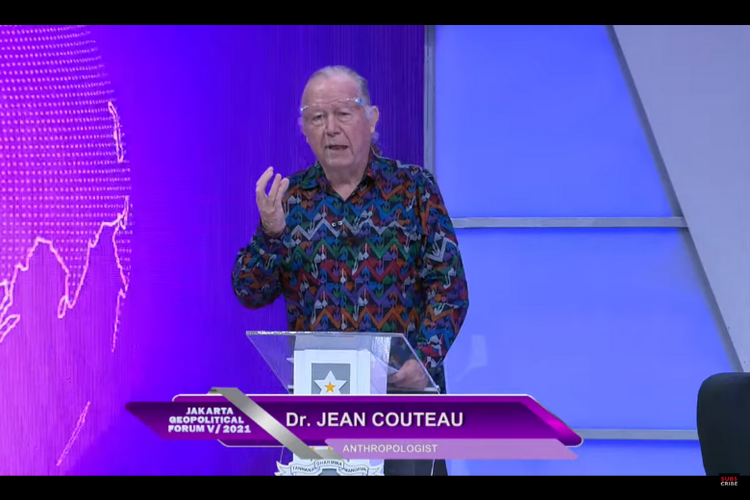 Antropolog Jean Couteau saat memaparkan materi.
Antropolog Jean Couteau saat memaparkan materi. Menurut Couteau, Gutenberg Sindrom sempat terjadi terjadi di negara Islam yang mana para aktivis menumbangkan rezim atau memaksa mereka mengadopsi politik Islamis saat praktik politik sekuler gagal membawa kemakmuran. Beberapa negara yang mengalami fenomena ini di antaranya Pakistan, Afghanistan, Iran, serta Irak.
“Fenomena tersebut juga terjadi di negara yang mayoritasnya Kristen, seperti sekte Lord’s Army di Uganda dan kaum evangelis di Amerika Latin,” kata Couteau.
Mengenai potensi terjadinya Gutenberg Sindrom di Indonesia, Couteau mengatakan bahwa situasinya cukup kompleks.
Menurutnya, jumlah orang miskin yang baru mengakses teknologi digital cukup banyak. Selain itu, ketidakpatuhan sekelompok orang terhadap pemuka agama dan ketidakmampuan pemerintah menyejahterakan masyarakat dan menerapkan keadilan sosial juga dapat menjadi pemicu.
“Meski demikian, Indonesia bukan Syria dan Lebanon. Indonesia memiliki ciri utama keindonesiaan, yakni lebih mengutamakan kebersamaan dibandingkan perbedaan,” katanya.
Sementara itu, Profesor Komaruddin Hidayat menjabarkan elemen pokok umat Islam di Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Elemen ini tidak dimiliki umat Islam lainnya di Timur Tengah. Elemen tersebut adalah kebebasan berserikat atau membuat gerakan rakyat di luar negara.
“Umat Islam di negara Timur Tengah lama hidup di bawah kekuasaan dengan model top and down atau piramida society. Sementara, umat Islam di Indonesia punya andil dalam memerdekakan republik ini,” ujar Komaruddin.
Menurut Komaruddin, memori kolektif yang dimiliki oleh umat Islam tersebut memiliki nilai positif, yakni umat Islam punya jasa besar untuk memerdekakan republik ini sehingga memiliki kompromi untuk menjadikan negara Indonesia bukan negara sekuler, meski juga bukan negara teokratik. Indonesia adalah negara republik.
“Hal tersebut membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki watak moderat. Dorongan dan dukungan untuk tetap menjalankan demokrasi dikawal oleh organisasi myarakat (ormas) terbesar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Lembaga Pendidikan tinggi di Indonesia. Jika ini berhasil dilakukan, Indonesia dapat menjadi model dan memberikan kontribusi besar dalam teori politik,” ujarnya.
Perkembangan sains jadi tantangan sekaligus peluang
Pada sesi pleno kedua Jakarta Geopolitical Forum, Robertus Robert memaparkan materi berjudul “Sains, Reflektivitas, dan Sains”. Dalam paparannya, kemajuan sains dan teknologi saat ini telah membawa potensi yang tak terbayangkan dalam masa depan manusia.
Ia melanjutkan bahwa di dalam peradaban modern, manusia dapat memperoleh keuntungan di beragam aspek dengan pemanfaatan teknologi dan sains. Namun, hal tersebut kembali lagi pada bagaimana manusia memanfaatkan teknologi dan sains.
“Virus corona yang melanda dunia saat ini merupakan akibat dari meluasnya intervensi manusia dengan menggunakan teknologi dan sains terhadap alam. Dampak dari kondisi alam yang kehilangan kemampuan memperbarui diri juga akan kembali pada manusia,” kata Robert.
Ironisnya, upaya untuk mengatasi dampak tersebut kembali dilakukan dengan teknologi. Akibatnya, manusia tidak dapat mempertimbangkan kembali dampak penggunaan teknologi.
Terkait penggunaan teknologi untuk kemanusiaan, Robert mengambil contoh dua sosok, yaitu Jeff Bezos dan Sarah Gilbert.
Jeff merupakan triliuner yang berhasil menambah pundi-pundi kekayaan selama pandemi dan melakukan liburan ke luar angkasa bersama keluarganya menggunakan roket buatan perusahaannya.
Sementara, Gilbert merupakan ahli vaksin dari Universitas Oxford yang menjadi idola kemanusiaan baru. Pasalnya, Gilbert berjasa memimpin penemuan vaksin AstraZeneca, vaksin Covid-19 yang paling banyak digunakan di dunia, dan tidak mengambil hak paten secara penuh.
“Dari dua sosok tersebut, kita menemukan dua jenis sikap pada era kapitalisme, globalisme, dan sains kontemporer. Jeff mencerminkan logika seorang kapitalis yang bermimpi untuk bisa piknik ke luar angkasa sambil mencari alternatif kehidupan baru di luar bumi. Sementara, Gilbert menghadiahkan dunia vaksin sebagai salah satu elemen penting untuk menghadapi krisis di dunia saat ini,” kata Robert.
Selanjutnya, dr Roslan Yusni Hasan memberikan pemaparan mengenai neuropolitics. Dokter yang akrab disapa Ryu Hasan tersebut menjelaskan soal politik dari sudut pandang sains. Hal ini terkait dengan bagaimana otak manusia membentuk pandangan politik.
 Dokter Ryu Hasan menjadi narasumber terakhir yang memaparkan materi pada sesi pleno kedua.
Dokter Ryu Hasan menjadi narasumber terakhir yang memaparkan materi pada sesi pleno kedua. Manusia dan beberapa hewan seperti simpanse dan mamalia belajar dengan meniru apa yang dilihatnya. Ia menambahkan, banyaknya mirror neuron pada otak binatang menyebabkan mereka bisa merasakan emosi individu lain. Hal ini dapat menimbulkan empati pada mereka.
“Empati merupakan dasar bagi moralitas. Adanya pandangan altruisme resiprokal pada manusia yang membuat mereka berkelompok karena otak kita memiliki banyak mirror neuron. Hal tersebut juga serupa dengan politik dan moral,” kata dr Roslan.
Dokter Roslan mengatakan, dengan kemampuan mengembangkan bahasa verbal, manusia mampu mengembangkan realita intersubyektif. Realita ini merupakan sebuah entitas yang muncul dari hasil imajinasi manusia dan kemudian menjadi kenyataan.
Ia memberikan contoh saat momen kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pada 17 Agustus 1945 pukul 7 pagi, Indonesia belum ada karena kemerdekaannya baru diproklamirkan pada pukul 10.00 WIB.
Realita intersubyektif, kata dr Roslan, dapat menjadi senjata bagi manusia karena dapat mengikat kelompok dalam jumlah besar. Bahkan, walau mereka tak saling kenal.
“Semakin besar jumlah kelompok, tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat realita intersubyektif supaya bisa mengikat kelompok sebesar mungkin. Bisa antarnegara dan antarras dari seluruh dunia menjadi satu kesatuan,” ujar dr Roslan.















